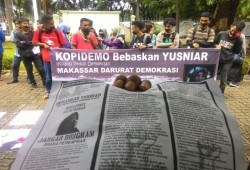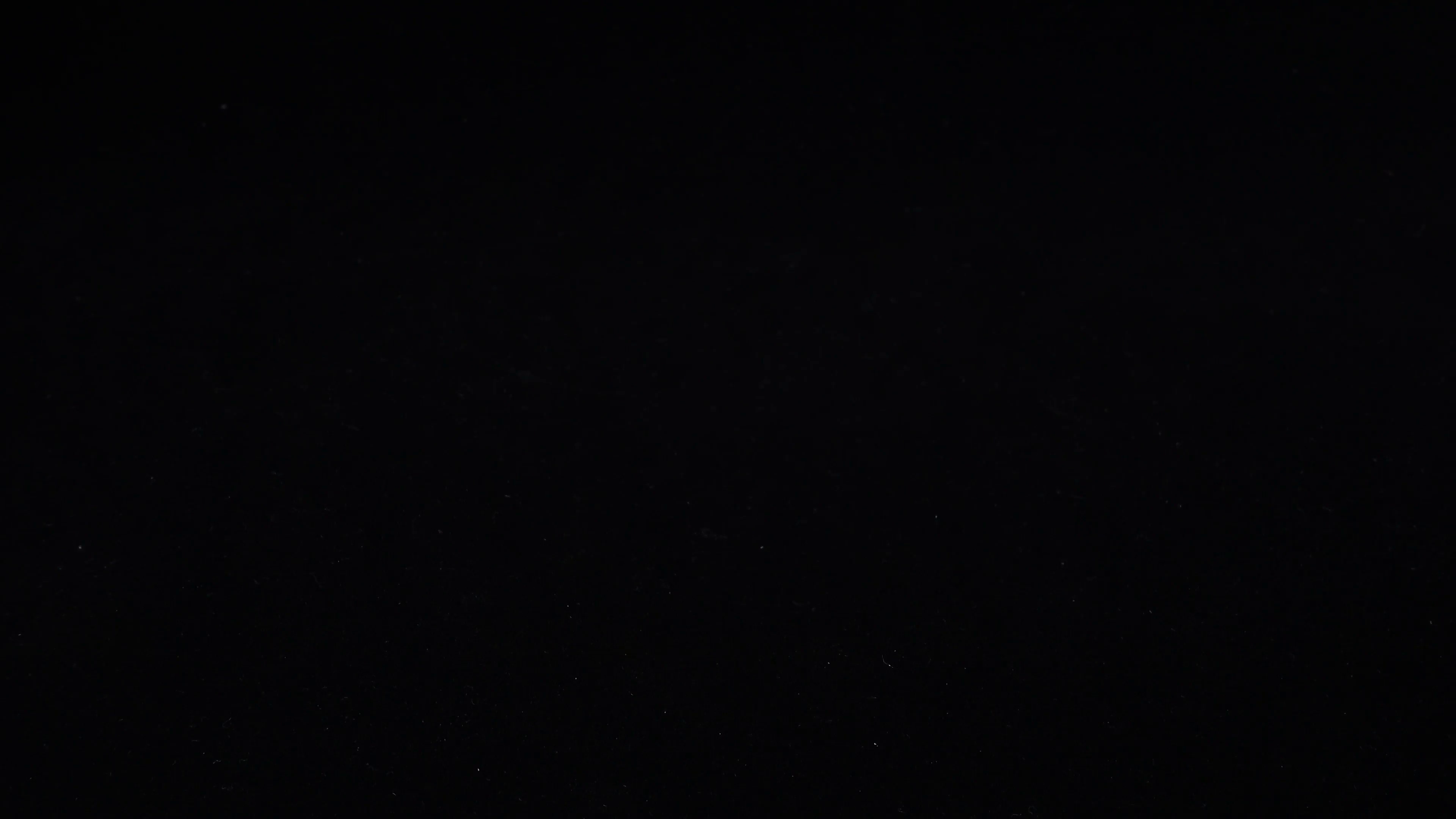Losari, ‘Tata Uang’ Mengatur Tata Ruang
Proyek CPI (Center Point of Indonesia) menjadi mega proyek di Makassar. Sayangnya, rencana itu akan mengorbankan begitu besar wilayah, yang dengan demikian akan memengaruhi segi lingkungan hidup dan sosial warga sekitarnya. Berikut tulisan ini merupakan bagian kedua dari diskusi Pantai Losari yang berlangsung pada 8 September 2012 lalu.
Faizal Ramadhan, peserta diskusi dari Anging Mammiri (Blogger Makassar) menyebut bahwa dua tahun sebelumnya sempat ia mendapati jajak pendapat tentang CPI yang berlangsung di Kampus Universitas Hasanuddin, Makassar.
Dalam pembahasan proyek CPI, disebutkan bahwa di dalam kawasan ini akan dibangun plasa, village, sampai tugu pahlawan. Bahkan, kata Faizal berdasarkan rencana yang ia simak di kampusnya, ada satu titik yang akan dipasangi sinar laser—yang bakal dipancarkan sebagai tanda ‘titik tengah’ Indonesia.
Biayanya tidak tanggung-tanggung: reklamasi mencapai anggaran Rp 150 miliar dan fisik hampir 500 miliar!“Reklamasi seperti itu, saya pikir, tren di kota-kota besar, seperti Abu Dhabi,” kata Faizal.
Jamak diketahui bahwa wilayah pesisir merupakan kawasan yang tidak bisa dikavling karena berfungsi ruang publik. Nah, jika demikian, bagaimana bisa proyek itu bisa terus berjalan? Sementara pula, tersiar kabar luas bahwa kawasan itu menjadi arena yang bermasalah lantaran beberapa pihak saling klaim memiliki petak dan luasan tanah di zona ini.
CPI dapat berdampak di wilayah sekitar Makassar. Dalam Google Map,telah tampak bahwa ada kondisi ekstrem di sekitar wilayah Makassar, seperti beberapa ceruk, yang ditengarai sebagai abrasi besar. “Sangat merusak wilayah sekitar Makassar. Pembangunan CPI dikhawatirkan dapat menambah gerusan di wilayah selatan (Makassar) bila bangunan sudah ada,” kata Ketua Ikatan Sarjana Kelautan Unhas, Kamaruddin Azis.
Kamaruddin mengungkapkan, kala masih bekerja di Walhi, ia bersama teman-temannya telah mengangkat tema lingkungan pesisir ini, seperti adanya pergeseran nelayan yang kian menyempit hingga ke Kayu Bangkoa, lalu ke Paotere, dan ke TPI Rajawali. Pada pertengahan 1990-an, kata Kamaruddin, pihaknya berupaya mengangkat tema maritim ke kalangan mahasiswa baru supaya semakin giat mengampanyekan konservasi lingkungan laut di sekitar Losari.
Pada pertengahan 1990-an, riset pemetaan lamun sepanjang Losari dilaksanakan. Hasil penelitian itu, papar Kamaruddin, menunjukkan bahwa lamun berkurang karena sedimentasi muara Sungai Je’neberang. Ini juga berlaku pada Sungai Tallo. “Mereka mengukur laju sedimentasi, mengukur bahan beracun di sekitar Losari, misalnya pada kerang-kerangan. Hasilnya, semua tidak layak dikonsumsi,” ungkap lelaki yang kerap dipanggil Daeng Nuntung ini.
Dari hasil penelitian Unhas disebut bahwa ada banyak spesies gastrophoda di muara SungaiTallo sekisar 7 kelas, sedang Sungai Je’neberang 11 kelas. Bicara kelimpahan, lebih banyak di Je’neberang daripada Tallo. Ada penurunan kualitas koloni. Untuk terumbu karang, berdasarkan laporan Jamaluddin Jompa, kualitasnya sangat jelek;di bawah 10 persen di sekitar Losari.
“Sebenarnya menarik memanfaatkan momentum hasil penelitian itu untuk melakukan konservasi, ditambah dengan kaitannya dengan isu tata ruang, saya kira, sangat berhubungan. Jadi kita tidak melulu bicara ketidakstabilan ekosistem.Lebih jauh menyangkut rehabilitasi,” Kamaruddin menyarankan.
Bicara Losari dan sekitarnya tentu harus pula mengaitkannya seperti ekosistem penopang hutan bakau. Sayangnya, kata Kamaruddin, laju eksploitasi bakau sampai ke wilayah Tanjung, Barombong juga sudah parah. Ini dikarenakan telah dikonversi menjadi kawasan permukiman.
“Rekomendasi kami, Losari dan sekitarnya harus dikembalikan fungsi ekosistemnya. Bisa kita pilih zona konservasi atau restocking biota. Dari sisi sosial ekonomi, bicara pemanfaatan, perlu ruang bebas untuk berbisnis di Losari. Jika melihat konstruksi bangunan, kelihatan tidak ada tempat lagi bagi nelayan padahal bagaimanapun kita harus menciptakan ruang agar semua elemen warga punya akses memanfaatkan Losari,” kata Kamaruddin.
Diapit Dua Sungai
Aktivis Walhi, Taufik, kemudian angkat suara. Ia mengharapkan ada perubahan pola berpikir tentang hubungan manusia dan alam sekitar. Untuk itu, kata Taufik, perlu ada pendekatan atau pertanyaan kosmologis dan religi: Tuhan menciptakan mana yang pertama, manusia atau alam?
“Tentu sebenarnya ruang. Jika bicara tentang ruang, ada dimensi, ada jarak di situ. Jeda waktu, semua dimensi dipadu menjadi ideologitas yang disebut ‘tata’. Artinya apa? Manusia adalah bagian dari ruang. Bicara tata ruang, jangan dulu bicara RTRW, tapi mazhab apa yang dipakai? Karena Makassar berbasis kapitalistik, maka kita tidak bijak di tata ruang. Tata uang mengatur tata ruang!” cetus Taufik.
Makassar dan Jakarta memiliki kemiripan. Kedua kota dibangun dengan model Eropa; kota yang ada di tengah-tengah sungai. Di Jakarta, berdasarkan studi yang pernah Walhi Jakarta lakukan, rupanya, Jakarta dan Makassar nyaris serupa dari hulu sampai hilir. Jakarta diapit Sungai Ciliwung dan Cisadaene, jika dirunut ke Puncak, jaraknya sampai 70kilometer dengan Pangrango sebagai daerah tangkap airnya. Di Makassar, ditarik ke atas sampai puncak, yakni Malino. Daerah tangkap airnya di Bawakareng dan Lompobattang. Kerusakan di Puncak sama dengan kerusakan di Malino. Dengan intensitas yang ada banjir kiriman bisa terjadi.
Elisa Tanudjaja, seorang arsitek yang bergiat di Rujak Center, Jakarta, memberi perbandingan bahwa Jakarta belakangan melakukan reklamasi pantai. Reklamasi itu dilakukan dikarenakan turunnya permukaan tanah di Jakarta bagian utara. Pertanyaan yang muncul, “Alasan kebutuhan apa sampai Makassar melakukan reklamasi pantai?”
“Apakah Makassar sebegitu sempitnya dengan pertumbuhan pendudukan hingga kita membutuhkan tanah baru?” tanya Elisa.[]