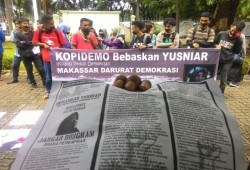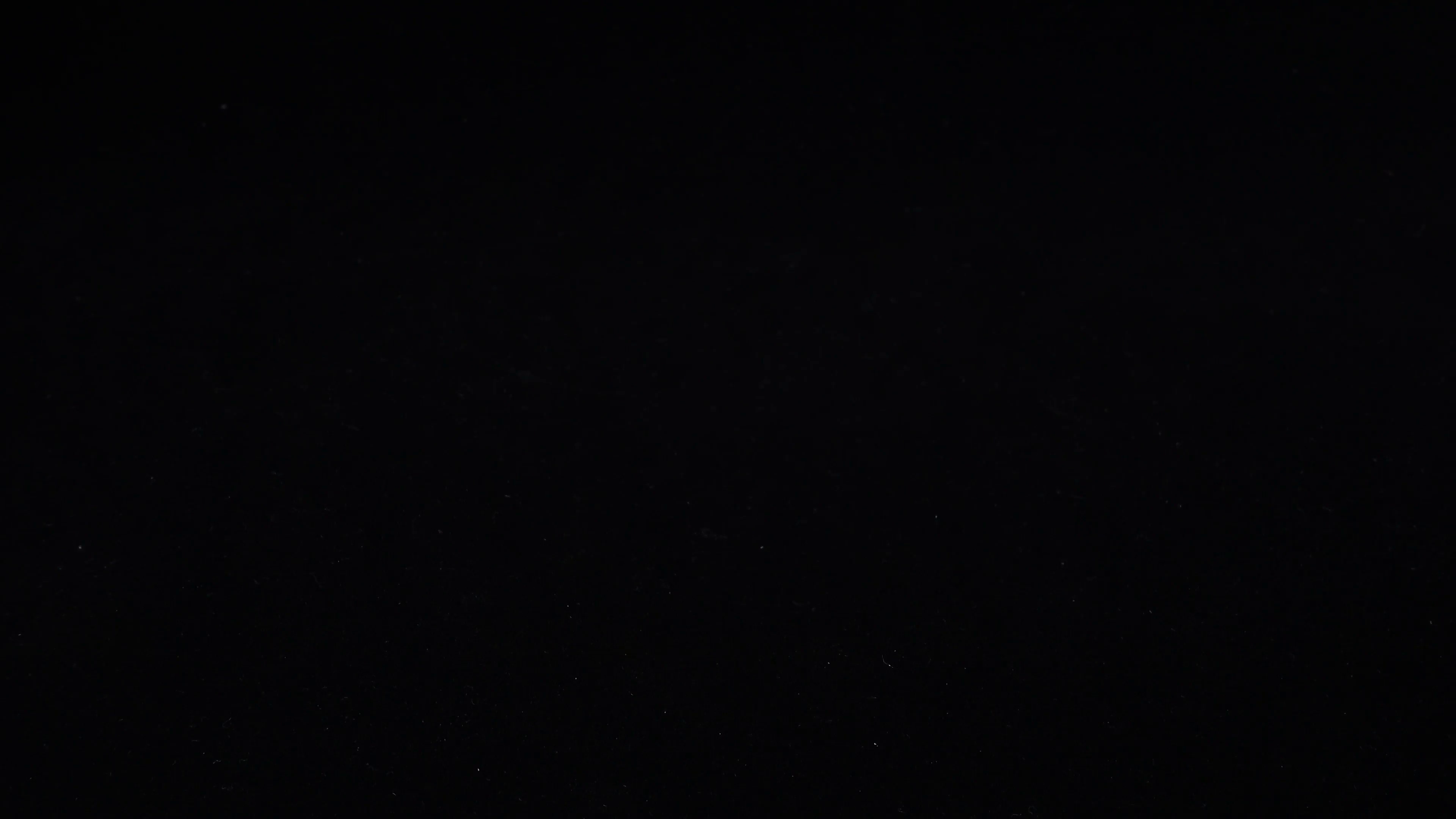Hikayat Dedaunan yang Diangkut ke Tenggara
La Heddang (60) memandangi rumah panggungnya di Desa Soga, Soppeng. Ia tampak diliputi kekhawatiran. Beberapa hari terakhir ia tak memproduksi ico, tembakau Bugis. Biasanya, di kolong rumah panggungnya, La Heddang mengolah tembakau kering, meracik ‘saus gula merah’, mencampur saus ke hasil rajangan tembakau, memasukkannya ke dalam timpo (wadah dari batang bambu) dan memanaskan campuran tersebut dalam oven khusus. Kali ini, ia tak punya cukup uang membiayai ongkos produksi. Khawatir pelanggan-pelanggan setianya tak memeroleh pasokan tembakau, ia memilih keluar desa.
Sudah bulat niatnya. Ia akan menempuh seratusan kilometer menuju Makassar menemui Haji Saide, seorang pengusaha tembakau Bugis ternama sekampungnya, Soppeng. La Heddang ingin bekerja beberapa minggu atau bulan di pabrik tembakau Haji Saide di Jalan Tinumbu, Makassar. Bagi Heddang, tak ada pilihan lain selain menjual kepiawaian. Kini amat sulit mencari pinjaman uang kepada pihak lain di desanya—sesuatu yang dulu tidak begitu susah ia peroleh. Awal Mei 2011 lalu, ia datang ke kantor desa dan memohon pinjaman sedikit modal dari kas desa. Tapi, sayang sekali, Kepala Desa Soga belum bisa memenuhinya.
Heddang menyalami istrinya.
Ia menelusuri Jalan Dusun Tonronge yang sudah jauh berbeda keadaannya. Empat dekade lalu, desanya marak tanaman tembakau. Di mana-mana orang-orang desa menanam, merawat, memetik, merajang, dan menjemur tembakau. Anak-anak hingga orangtua menjadi bagian dari budaya tembakau. Kini mereka menjadi petani kakao. Salah satu perbedaan mencolok adalah tiadanya budaya situlung-tulung antar keluarga dan rumah tangga di desa ini. Jelas, bagi desa ini, budaya kakao lebih berwatak individualis dan budaya tembakau cenderung komunal. Kakao adalah komoditas ekspor, sementara tembakau Bugis hasil bumi yang lebih banyak dikonsumsi secara lokal.
La Heddang juga menanam tembakau masa itu. Ia membeli bibit lalu menanamnya di lahan khusus yang telah digemburkan bersama dengan kawan-kawan petaninya. Dengan lahan sehektar, mereka menanam 10.000 bibit selama dua-tiga hari. Mereka kemudian menutupi tanaman itu dengan berlembar daun enau selama 14 hari. Guna menghindari hama kalanrei yang dibawa oleh semut, ia menyemprotkan pestisida. La Heddang membutuhkan empat botol pestisida untuk sekali semprot (Rp 2.500/botol).
Setelah tumbuh pucuk daun kedua, ia akan memotong (iceleppiri) daun pertama dan membiarkan daun kedua melebar. Demikian pula pucuk-pucuk baru di dekat daun ia akan memotongnya hingga akhirnya terdapat delapan lembar daun dalam satu tanaman yang dijaga pertumbuhannya. Jika tanamannya sudah mencapai ketinggian 75 sampai 100 cm, ia menyemprotnya lagi setiap minggu selama dua bulan hingga daun tembakau siap petik.
Kaum perempuan desa lalu memetik daun tembakau. Mereka menyimpannya 4 hari sebelum dirajang, dijemur, dan digulung. Setelah itu, lahan akan ditanami tanaman sela, umumnya jagung sebagai makanan pokok petani atau membiarkan lahan istirahat tanpa penanaman.
Tiba giliran laki-laki bekerja. Mereka bertugas merajang daun tembakau (makkire’ ico) menggunakan pisau khusus dan kattang (tempat perajangan setumpukan daun tembakau). Sementara yang menebar rajangan tembakau (mattale’ ico) di alas penjemuran (tabba atau jamba’) berukuran 80 cm kali 120 cm adalah kaum perempuan. Setelah rajangan tembakau siap dijemur, segera anak-anak mereka akan meraihnya dan membawanya ke luar kemudian menjemurnya di sepanjang jalan di depan rumah mereka.
Setelah dua hari terpanggang matahari, rajangan tembakau tadi akan kering dan anak-anak atau kalangan remaja akan menggulung daun-daun tembakau ini dari kedua sisi. Gulungan dari sisi kiri dan kanan bertemu tepat di bagian tengah gulungan. Gulungan ico dari setiap ta’ba’ akan ditumpuk hingga beberapa tumpukan. Inilah akhir kerja petani dan pekerja daun tembakau.
Setelah itu, para pekerja Haji Palerei, akan datang membeli seluruh gulungan tembakau itu dan memrosesnya menjadi Tembakau Bugis. Haji Palerei adalah pemasok tembakau untuk wilayah timur dan tenggara Sulawesi.
Ingatan La Heddang berhenti saat di kejauhan sana sebuah angkutan desa mendekat. Ia melambai menghentikan mobil itu. Ia menuju Takkalalla, kota kecamatan, tempatnya akan menumpang oto panter, angkutan umum antar kabupaten, menuju Makassar.
Di sepanjang jalan yang dilewatinya, La Heddang hanya melihat barisan pohon kakao berusia tua. Dari dusun satu ke dusun lain, dari desa satu ke desa lain. Tak satu batang pun tanaman tembakau—sebagaimana yang ia tangkap dalam kenangannya.
Tapi angannya belum tuntas. Sekali lagi ia bergerak ke masa silam. Di masa ketika ekonomi tembakau mengubah budaya hidup mereka. Sebuah budaya tanam baru yang perlahan-lahan membuat kakatua (cakkelle) dan ‘burung putih’ (putteng) tak betah lagi di desa. Ia masih ingat, kedua jenis burung yang memakan jagung dan kacang hijau itu mudah ditemui saat itu. Ketika tembakau menggulung dua tanaman itu, persediaan makanan kedua burung itu terputus dan akhirnya pergi, meninggalkan penduduk yang tengah mengelukan idola baru: ico.
Haji Palerei merupakan pemasok tembakau Bugis bagi perokok di wilayah timur dan tenggara Sulawesi. Padanyalah Heddang muda belajar memproses ico dan membantu distribusi rokok Haji Palerei ke Kolaka, Kendari, Buton, dan Raha (Sulawesi Tenggara). Para petani tembakau juga memasok daun ico untuk Haji Palerei.
Haji Palerei dengan 20 pegawainya, memproduksi seratus timpo tembakau Bugis sehari. Satu timpo berisi 20 gulungan tembakau kering. Dari setiap gulungan, seorang perokok tembakau dapat melinting hingga seratus batang.
Haji Palerei seorang pedagang inovatif. Kabarnya, dialah yang memulai mencampur ico dengan saus gula merah—yang saat itu masih diproduksi oleh banyak pembuat gula dari pohon aren—dan membakarnya di dalam timpo (batang bambu) yang dibuat di wanua (kampung) Soga pada era 1970-an. Sebelumnya, tembakau Bugis bentuknya gulungan tembakau kering.
Rute pengangkutan tembakau Bugis dari Soga ke Sulawesi bagian tenggara menggunakan patteke (angkutan kuda) ke Koppe, lalu dengan mobil ke Pelabuhan Bajoe, menyeberang dengan perahu lambo ke Kolaka dan mengarah ke Kendari dengan truk, kemudian menyeberang lagi dengan perahu lambo ke Pulau Muna, dan akhirnya sampai ke Bau-Bau, di Pulau Buton. Ketika komoditas tembakau mengalami kemunduran dan, setelahnya, saat tidak semua orang Soga punya lahan cukup untuk menanam kakao, mereka pun merantau ke Tenggara dengan membuka lahan baru. Sebagian mereka kini hidup berkeluarga di Kolaka.
Haji Palerei (80), kini menekuni komoditas kakao, menetap di Kabupaten Kolaka. Sebagai pedagang tembakau Bugis yang sukses, ia memiliki banyak alat produksi seperti truk, mobil Toyota pick-up dan lahan yang luas di beberapa tempat, seperti Wanua Soga maupun di desa-desa di Kolaka. Sejak tanaman tembakau memudar pada pertengahan 1980-an, tak ada seorang pun petani Soga menanam tembakau. Mereka kini menanam kakao sebagai sumber pendapatan ekonomi baru. Tapi La Heddang bertahan menekuni komoditas yang surut masa jayanya itu. Di desa lain, seperti Cabbenge, masih banyak petani menanamnya. Ia tak khawatir dengan pasokan daun ico.
Heddang kini di atas panter menuju Makassar. Empat atau lima jam kemudian ia akan menemui H. Saide dan menyampaikan maksudnya.
Saide bisa disebut seorang legenda. Ia mendirikan Perusahaan Rokok Adidie tahun 1962 di Makassar. Hingga di usianya yang kesembilan puluh, perusahaan ini terus berproduksi. Bahan baku Adidie ia dapatkan dari Cabbenge, desa kelahirannya. Masa jaya usahanya pada 1970 sampai awal 1990 menjadikan H. Saide salah seorang dari sedikit orang terkaya di Sulawesi Selatan. Tembakau buatannya dikenal rokok beraroma keras (sarru’, dalam bahasa Makassar) yang paling diminati oleh para perokok Sulawesi hingga Papua pada dua sampai tiga dekade lalu.
Saide muda memilih meninggalkan Cabbenge, ketika tanah kelahirannya diduduki laskar DI/TII. Sebagian besar penduduk mengungsi ke kota yang berada di bawah kendali militer Siliwangi yang bertugas melawan pembangkangan politik Qahhar Mudzakkar. Saide sendiri memilih mengungsi ke Makassar pada tahun 1955 dan beberapa tahun kemudian mengembangkan usaha ico-nya, dengan pasokan tembakau dari desa-desa di Soppeng, khususnya Cabbenge.
Saide adalah putra ketiga dari pasangan H. Bocing dengan I Cue’. Saudaranya berjumlah 6 orang, tapi hanya dia yang menggeluti tembakau. Ia menikah dengan Hj. Sitti dan dikaruniai sembilan putra dan seorang putri. Setelah perjuangan DI/TII mengendur dengan tewasnya Qahhar Mudzakkar di Sungai Lasolo, Kolaka, keadaan kampung-kampung di Sulawesi Selatan lebih tenang. Banyak pengungsi kembali ke desa dan menanam tembakau. Memasuki tahun 1965, saat kondisi keamanan semakin kondusif di desa, usaha H. Saide mulai bertumbuh, dan semakin stabil hingga tahun 1980-an.
Kekayaan H. Saide dari hasil usaha tembakaunya terlihat jelas. Ia memiliki beberapa rumah besar baik di kampung halaman, di Makassar, maupun di Jakarta. Ia juga membeli sejumlah mobil mewah di masanya semisal Jeep Willis, VW, dan Chevrolet. Belum lagi alat-alat produksi untuk menopang proses produksi dan distribusi tembakaunya ke luar Makassar. Dengan jumlah pekerja tembakau berkisar 40 orang yang menghasilkan 500 timpo tembakau per hari, ia menjadi pengusaha rokok terbesar di Sulawesi Selatan. H. Saide bahkan pernah membangun usaha bisnis transportasi publik (bis) rute Soppeng – Makassar – Sinjai. Tapi usaha sampingan itu ia tinggalkan dan memilih berkonsentrasi pada usaha tembakau.
Beberapa pengusaha ico lain yang turut berkembang saat itu antara lain: H. Kasiran (Rokok Tempe), H. Santo (pabriknya bersebelahan dengan Pasar Terong, Makassar), H. Hafid (di Batua Raya, Makassar), H. Indare (Rokok Doanja, Cabbeng), H. Nasir (Rokok Ayam Telor, Cabbenge), dan, tentu saja, H. Palerei di Soga. Keluarga-keluarga ini dan umumnya keluarga lain yang terlibat langsung dalam produksi tembakau. Generasi kedua mereka menikmati kemakmuran yang tak pernah dirasakan generasi sebelumnya.
Salah seorang dari generasi kedua itu adalah Sudirman Nasir (41), putra H. Nasir. Ia kini dosen pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Di awal 1990-an, ia adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, sebelum melanjutkan studi master dan doktoral di Australia.
Sebagai anak pengusaha tembakau, biaya pendidikan tentu bukan masalah. Demikian pula ketika salah seorang putra H. Saide melanjutkan kuliah di Jakarta pada dasawarsa 1980-an, mudah saja baginya membeli sebuah rumah mewah di kawasan Menteng. Kabarnya, kini rumah milik H. Saide itu sudah bernilai belasan miliar rupiah.
Bagi Sudirman, masa jaya tembakau Bugis memang telah lewat. Sebagian yang bertahan dan tetap hidup makmur sekarang bisa melakukannya karena bertindak antisipatif. Maksudnya, selain berdagang tembakau, sebagian modal mereka alihkan untuk membeli tanah sawah dan kebun, di Soppeng atau di luar Soppeng. Sudirman menyebut beberapa pengusaha tembakau yang masih bertahan karena sikap antisipatif mereka. Mereka adalah keluarga H. Indare’ (pengusaha rokok merek Doanja), keluarga H. Saing dari Mattirowalie dan keluarga H. Saide di Makassar. Sedangkan sebagian keluarga lain sedang menghadapi masalah generasi kedua, yakni generasi yang sekadar hidup foya-foya di saat masa jaya orangtua mereka.
Pada masa jaya itu, ketika ia masih berusia belasan, Sudirman melihat remaja-remaja dari keluarga tembakau di Cabbenge sudah terbuai oleh mobil-mobil mengkilap dan sepeda motor terbaru. Sehari-harinya mereka memamerkan mobil berikut asesorisnya dan maccewe’-cewe’ atau berpacaran saja. Jika ada keluaran mobil terbaru di Jakarta, pastinya tak lama akan tiba di Cabbenge.
“Aih, napabbangkerro’i tomatoanna (Wah, mereka membangkrutkan orangtua)!”keluh Sudirman dalam bahasa Bugis. “Deteriorating rapidly and now unemployed! (memburuk dengan cepat dan kini menganggur),” demikian simpul Sudirman, dalam bahasa Inggris, tentang generasi kedua dari keluarga pengusaha ico yang runtuh.
Runtuhnya usaha ico berbasis keluarga ini juga diperparah oleh ekspansi rokok dari Jawa, khususnya kretek dari Kudus. Dibandingkan dengan kretek, ico nyaris kalah dalam semua aspek. Mulai dari kemasan yang lebih baik (olahan mesin), aroma yang lebih bercita rasa (campuran cengkeh), manajemen usaha yang lebih profesional (usaha kretek sudah mulai pada abad ke-19 sejak ditemukan pertama kali oleh H. Jamhari dan dikembangkan oleh H. Nitisemito), dan tentu saja harga yang terjangkau dengan sisi kepraktisan yang jauh lebih memanjakan konsumen.
Di Makassar, hanya ‘Adidie’ milik H. Saide yang bertahan. Di usia sepuhnya, H. Saide bersama 6 pekerjanya hanya mampu memproduksi 300 timpo/minggu atau 1.200 timpo/bulan atau 14.400 timpo/tahun. Bandingkan pada masa jayanya dengan produksi mencapai 15.000 timpo/bulan dan 180.000 timpo/tahun. Jika dahulu pekerjanya mencapai 40 orang, kini tinggal 6 orang saja. Jika dulu distribusi tembakaunya ke Indonesia bagian timur, kini semakin menyempit di sebagian kecil area Sulawesi Tengah dan Selatan. Jika dulu konsumennya dari berbagai kalangan, kini tinggal sebagian petani dan nelayan saja yang mengisapnya. Jika dulu harga belinya menguntungkan pengusaha dan pedagang eceran, kini harganya jauh merosot.
Bagi H. Muhammad Nur, akhir dari usaha rokok Adidie tinggal menunggu waktu. Begitu H. Saide tutup usia, maka cerita seorang legenda rokok akan tamat.
***
Sore, setibanya di Terminal Daya Makassar, Heddang melanjutkan perjalanan menuju Jalan Tinumbu. Ia naik pete-pete menuju Pasar Sentral. Di ujung Jalan Tinumbu, ia berjalan menuju Pabrik Rokok Adidie. Di depan sebuah bangunan serupa rumah toko ia berdiri. Sejenak ia membaca papan nama di sudut kanan atas rumah ini. Tertulis di sana ‘Perusahaan Rokok Adidie’ berdiri sedjak 1962’. Ia maju beberapa langkah, mengetuk pintu dengan mantap untuk satu tujuan pasti, mengumpulkan modal untuk melanjutkan usaha tembakau Bugis di kolong rumah panggung yang ia tinggalkan tadi pagi.[]