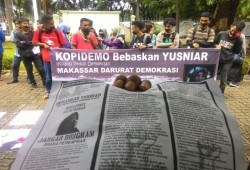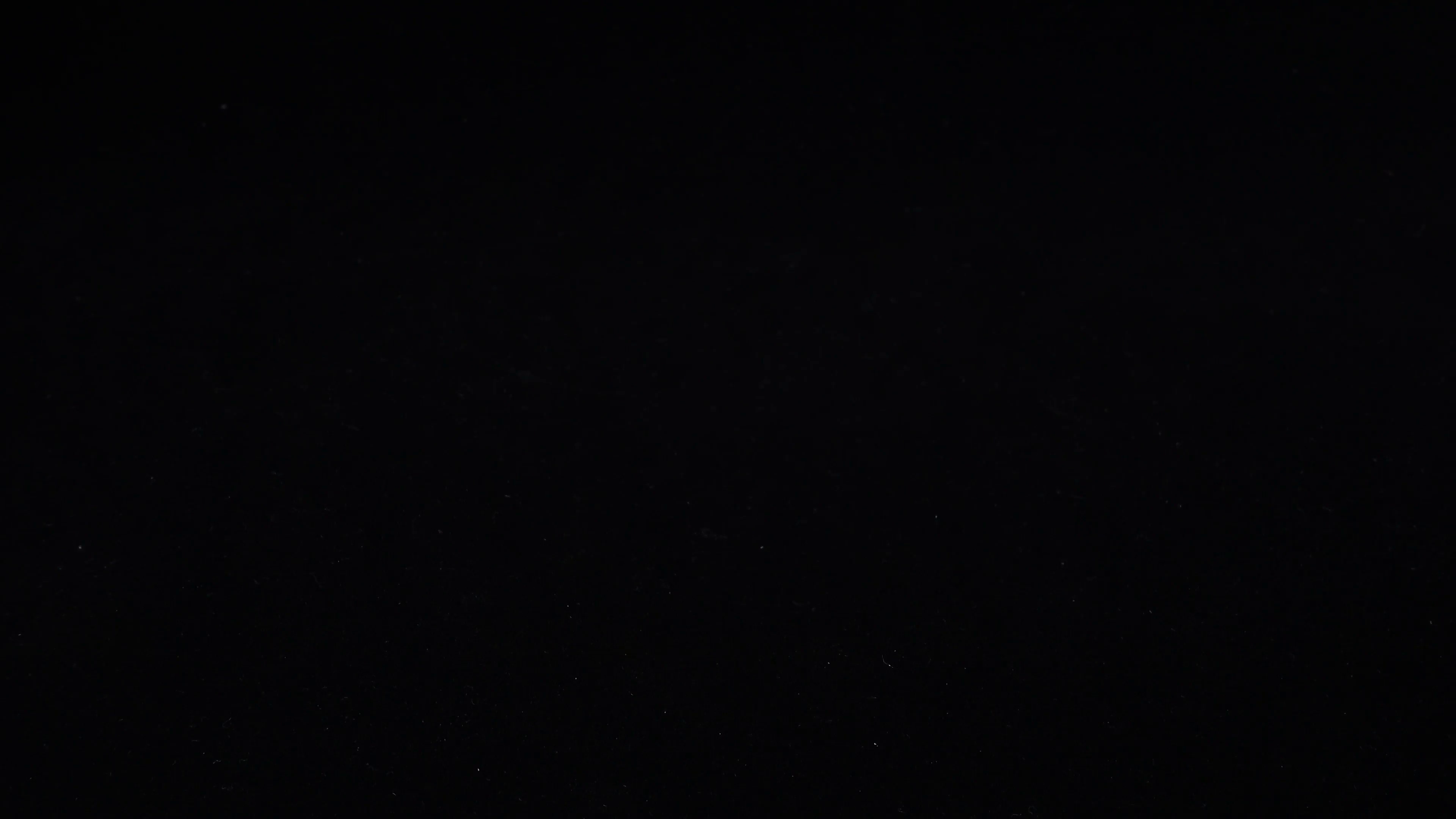Hidangan Beracun dari Gunung Sampah

Gundukan sampah di TPA Antang dengan berbagai problematikanya adalah hal yang meresahkan, juga memberi kita gambaran seberapa besar kontribusi industri yang menggunakan kemasan plastik dalam mempengaruhi gaya hidup konsumtif, hingga menghasilkan sampah. Bahwa di samping embel-embel eco friendly yang melekat dalam kemasan produk ataupun citra perusahaan, tetap saja sampah mereka berakhir di TPA tanpa pengelolaan.
Sebelum Tamangapa dibangun sebagai lahan TPA pada 1979, sampah padat perkantoran Makassar dibuang di Panampu, Kecamatan Ujung Tanah. Karena keterbatasan wilayah dan lokasinya yang dekat dengan laut, tempat pembuangan sampah pun dipindahkan ke Kantisang, Kecamatan Biringkanaya pada 1980, karena menurunkan kualitas air. Pada 1984, pemerintah Makassar membangun TPA baru di Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate. Tetapi pertumbuhan penduduk dan pengembangan perumahan sekitar Kecamatan Tamalate mendorong pemerintah untuk membangun Tamangapa sebagai lahan TPA untuk Kota Makassar pada tahun 1992. Dari catatan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Makassar, TPA yang beroperasi sejak tahun 1993 silam dengan luas wilayah 14,3 hektare saat itu. [1]
Bau busuk dan macet adalah dua hal yang identik di sepanjang Jalan Tamangapa Raya. Sumber bau terhirup karena gas metana (CH4) yang dihasilkan dari tumpukan sampah di TPA. Tumpukan sampah juga menyebabkan kemacetan, terutama karena gerombolan sapi yang jadwal pulang dan pergi mereka mengais makan di TPA bertepatan dengan waktu-waktu padat lalu lintas. Rombongan sapi ini biasanya terdiri dari sepuluh hingga lebih, tidak akan bergeser meskipun klakson motor dibunyikan berkali-kali.

Hal lain yang akan menemani perjalanan lalu lintas pengendara di kawasan ini adalah debu-debu dari kendaraan besar, baik itu mobil pengangkut sampah ataupun mobil yang mengangkut pasir. Keluhan semacam ini muncul dari mereka yang, mau tidak mau, harus melintasi jalan tersebut.
Saya ingat, pada 2019 silam, semasa saya masih menjadi mahasiswa baru Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, teman sekelas juga dosen yang akan mengisi kelas di hari itu bercerita bahwa kabut asap masih terlihat jelas di sekitar TPA Antang. Rupanya itu karena kebakaran yang terjadi pada Minggu siang, 15 September 2019. Lima belas armada pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api, hingga Senin subuh, 16 September 2019. Setelah 15 jam pemadam berjibaku, barulah api dapat ditaklukkan.
Menurut pengakuan warga sekitar, meskipun api berhasil dipadamkan, kabut asap masih mengepul selama kurang lebih dua minggu pasca kejadian dan empat hari pertama menimbulkan asap tebal. Selama dua minggu itu pula, keluhan-keluhan terkait polusi kebakaran terdengar riuh bagi mereka yang harus melintasi kawasan tersebut.
Insiden kebakaran TPA tahun 2019 bukanlah kejadian baru. Hingga Agustus 2024, tercatat sudah terjadi enam kali kebakaran: 29 Juni 2009, 3 Oktober 2014, 10 Oktober 2018, 15 September 2019, dan 27 September 2022. Namun, peristiwa tahun 2019 tergolong kejadian yang paling parah.
Penyebab kebakaran tidak pernah terungkap. Simpang siur warga menduga bahwa api bersumber dari puntung rokok pemulung atau awak truk sampah. Sayup-sayup informasi bahwa TPA sengaja dibakar karena overcapacity. Tetapi hingga sekarang belum ada yang tahu kebenarannya. Satu yang pasti, gas metana dari timbunan sampah di TPA sangat mudah tersulut api.
Limbah padat perkotaan yang tersimpan pada saat pertama kali dibuang ke landfill akan mengalami tahap pemecahan bahan organik oleh mikroorganisme yang membutuhkan oksigen dalam proses penguraian. Kurang dari satu tahun kondisi anaerob (kondisi tanpa oksigen) mulai terbentuk dan bakteri penghasil metana mulai menguraikan limbah hingga menghasilkan metana.[2]
Kepala UPT TPA Antang, Nasrun, menyampaikan bahwa setiap harinya TPA memproduksi sampah sebanyak 800-1000 ton.[3] Menurut Erina Dwi Ramadhani (2022), sekitar 69,56% dari sampah tersebut merupakan sampah organik. Berdasarkan data tersebut, jumlah sampah organik yang dihasilkan TPA Antang mencapai 695,6 kg/hari. Secara teori, setiap kilogram sampah organik dapat memproduksi 0,5 m3 gas metana.[4] Dengan demikian, kalkulasi total gas metana yang dihasilkan oleh TPA Antang adalah 126.947 m3/tahun. Angka tersebut ibarat mata pisau; dapat memberikan manfaat atau menimbulkan bahaya, tergantung pada pengelolaannya.

Sebagai komponen utama gas alam, metana adalah sumber bahan bakar utama. Berbagai penelitian menjelaskan bahwa gas metana dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif, salah satunya sebagai pengganti bahan bakar LPG. Secara matematis kandungan energi gas metana TPA Antang sebesar 126.947 m3/tahun senilai dengan sekitar 200.204 m3 LPG/tahun, sebanding dengan 50.051 buah tabung LPG 3 kg dihasilkan TPA Antang dalam kurun waktu setahun.
Sayangnya, pengelolaan gas metana di TPA belum maksimal, sehingga keberadaannya justru menimbulkan bahaya. Berdasarkan data dari Dinas Kebersihan Pemerintah Kota Makassar (2007), pada TPA terdapat fasilitas pengumpul gas tipe PVC. Pipa ini diperuntukkan untuk mengontrol gas metana agar tidak terjadi ledakan atau kebakaran. Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh Andi Fahdina Fitrianti (2014) mengungkapkan bahwa pipa-pipa tersebut sudah tidak berfungsi lagi.[5] Hal ini selaras dengan hasil kunjungan lapangan mahasiswa Departemen Teknik Lingkungan Universitas Hasanuddin pada 1 Juni 2023, dosen praktisi yang mendampingi mengatakan bahwa sebagian besar pipa-pipa tersebut hilang, kemungkinan besar karena dicuri, mengingat akses keluar masuk ke TPA yang relatif mudah.
Metana tidak dapat diserap secara alami oleh klorofil dalam proses fotosintesis. Sifatnya yang mudah terbakar, membuat kontak antara metana dan api dapat memicu ledakan. Tidak hanya pada lingkungan, gas CH4 juga berbahaya apabila terhirup manusia. Efek samping yang dapat dirasakan dapat berupa mual, sakit kepala, detak jantung lebih cepat. Masalah kognitif juga dapat terjadi seperti kehilangan memori, penglihatan kabur, gelisah, lesu dan lain sebagainya.[6]
Jika ‘hanya’ paparan asap, debu, dan dampak lainnya bisa membuat jengkel pengendara, lantas bagaimana dengan mereka yang bermukim di sekitar daerah operasi TPA? Paparan polusi yang mereka peroleh tentu akan berlangsung lebih lama dibanding mereka yang sekadar melintas. Hal ini yang mendasari saya untuk mencari tahu seberapa berdampak kejadian tersebut terhadap kesehatan pernapasan mereka.
Ikbal, B (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kebakaran menghasilkan ratusan senyawa berbahaya seperti karbon monoksida, formaldehid, nitrogen oksida, sulfur oksida serta senyawa bau yang sifatnya iritan, hasil dari pembakaran yang tidak sempurna. Dijelaskan formaldehid dapat memberikan dampak berupa mata berair, sensasi terbakar pada mata dan tenggorokan, mual, kesulitan bernapas, ruam kulit, serta dapat menyebabkan kanker. Selain itu, berbagai macam zat beracun dapat dilepaskan ke lingkungan dari limbah yang tidak terkontrol di pembuangan sampah seperti metana, karbon dioksida, benzene, dan kadmium. Banyak dari polutan ini terbukti menjadi racun bagi kesehatan manusia.7
Pada Sabtu, 17 Agustus 2024, saya mencari informasi mengenai situasi di TPA Antang. Rekan saya yang kebetulan warga Antang bercerita bahwa neneknya terkena ISPA dan harus rutin cek kesehatan dan mengonsumsi obat lebih dari lima tahun. Nenek teman saya itu berusia 74 tahun, tinggal di Perumahan Graha Borong Jambu, berjarak 450 meter dari TPA. Ini hanyalah satu dari sekian banyak kasus penyakit ISPA yang ada di masyarakat sekitar TPA.
Wilayah operasional TPA Antang sangat dekat dengan permukiman. Jarak terdekat dengan menarik garis lurus melalui aplikasi citra satelit hanya 103 meter, sedangkan jarak sungai terdekat dengan lokasi TPA ini hanya berjarak 895 meter. Perumahan terdekat dari TPA adalah Perumnas Antang, Perumahan TNI Angkatan Laut, Perumahan Graha Borong Jambu, Perumahan Griya Tamangapa, dan Perumahan Taman Asri Indah.
Menurut Asiri (2019) keberadaan TPA berdampak pada kesehatan yang relatif sangat mengganggu dan penyakit yang ditimbulkan cukup serius, seperti ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Atas) meskipun usaha-usaha pengobatan cukup dilakukan.8
Berdasarkan data Puskesmas Antang, penderita penyakit ISPA pada 2018 terdapat 1764 kasus, 3179 kasus (2019), 1911 kasus (2020), dan 787 kasus (2021). Untuk Puskesmas Tamangapa sendiri pada tahun 2019 terdapat 3490 kasus penyakit ISPA, 1634 kasus (2020), dan 1329 kasus (2021). Jumlah kasus ISPA terbanyak terlihat di tahun 2019, bertepatan dengan kebakaran TPA yang paling parah.
Untuk memperoleh informasi dari mereka yang terpapar penyakit ISPA sangatlah sulit. Banyak dari mereka yang mungkin tidak sadar kalau sudah terpapar. Hal ini sejalan dengan hasil perbincangan saya dengan beberapa warga yang tinggal kurang dari 100 meter dari lokasi TPA.
Saat mencoba mencari tahu apakah mereka punya gejala ISPA seperti gejala batuk kering atau berdahak, pilek dan hidung tersumbat, sakit tenggorokan, demam disertai keringat dingin, nyeri di bagian kepala ataupun gejala lainnya. Banyak di antara mereka menimpali bahwa gejala itu sering mereka alami. Hanya saja memilih tidak ke dokter dan menunggu sampai kondisi mereka pulih sendiri. Jadi sulit mendiagnosa apakah gejala tersebut disebabkan ISPA atau penyakit lainnya, meski data puskesmas yang melayani warga sekitar TPA menunjukkan jumlah warga terjangkit ISPA tergolong banyak.
Pada hari kedua penelusuran, saya bertemu perempuan paruh baya, kisaran 50-60 tahun. Identitasnya tak ingin ditayangkan. Ibu ini adalah warga asli yang tinggal di tempat tinggal non permanen tak jauh dari TPA. Ia berada di situ karena terdapat kebun garapannya bersama keluarga.
Ia mengaku tidak pernah mencoba peruntungan sebagai pemulung di TPA. Mayoritas pemulung justru pendatang; kebanyakan dari Jeneponto, Sinjai, Bulukumba, Gowa, dan Takalar.
“Orang-orang di sini gengsian. Jadi kebanyakan yang jadi pemulung itu pendatang. Tetapi di kampungnya mereka, itu pemulung dikenal berada. Makan mi gengsimu!” cetus si ibu sembari tertawa.

Banyak dari mereka yang berhasil membeli tanah di daerah tersebut, hingga membentuk perkampungan, lalu diberi nama Kampung Kajang dan Kampung Bugis. Kampung Kajang terletak di RT 04 Kelurahan Tamangapa, sedangkan Kampung Bugis terletak di Jalan Amd Tamangapa. Seperti namanya, Kampung Kajang dihuni perantau yang mayoritas berasal dari Kajang, Bulukumba. Beberapa ada yang dari Jeneponto dan daerah campuran lainnya. Penyematan nama ini karena penghuni pertama kampung tersebut adalah pasangan suami istri—sang suami berasal dari Bone dan istrinya dari Kajang, Bulukumba.
Sedangkan Kampung Bugis dihuni perantau mayoritas suku Bugis. Akulturasi budaya juga terjadi dalam lingkungan ini, ditandai oleh pernikahan antara warga lokal dan pendatang. Salah seorang anak ibu tersebut juga pernah menikah dengan seseorang yang berasal dari Bulukumba sebelum akhirnya sepakat berpisah.
Beberapa pemukim Kampung Kajang dan Kampung Bugis profesi utamanya adalah buruh tenaga angkut, awak truk sampah, sebagian tenaga honorer dan pegawai negeri sipil di Dinas Kebersihan. Bagi mereka yang kebutuhan ekonominya belum tercukupi, akan dibantu oleh istri mereka dengan memulung di TPA.
Aktivitas pemulung dibagi menjadi dua jadwal, yaitu pagi dan malam. Hingga dini hari TPA masih ramai dengan aktivitas para pemulung. Terlebih lagi, sampah dari perkotaan tetap masuk ke TPA dibawa oleh pengangkut yang shift malam.

“Di dalam itu ramai perempuan yang pilih-pilih sampah. Yang shift pagi dapat giliran dari jam 05.00 pagi-16.00, shift malam dari jam 17.00 sampai jam 04.00 subuh, tetapi biasanya paling ramai sore-sore jam 16.00 sampai jam 04.00 subuh. Kalau dijual ada yang penghasilannya Rp 150.000 per hari,” beber ibu yang enggan disebutkan namanya.
“Banyak dari mereka yang pakai untuk kebutuhan pokok. Tetapi ada juga yang dikenal sukses, bahkan sampai naik haji gara-gara mulung,” lanjutnya.
Di dalam TPA, jalur-jalur yang mulanya menjadi tempat lalu lintas truk untuk menuju tempat bongkar muat sampah perlahan menghilang dan diisi tumpukan-tumpukan sampah yang baru. Kepala UPT TPA Dinas Lingkungan Hidup, Nasrun mengungkapkan tumpukan sampah di TPA telah melebihi kapasitas, bahkan ketinggian tumpukan sampah sudah mencapai 30 meter atau setara dengan gedung 12 lantai, bahkan beberapa referensi menyebutkan ketinggiannya telah mencapai 50 meter. Menurut Nasrun, setiap hari hampir sekitar 500 pemulung yang mencari sampah di TPA.9
Dari depan gerbang TPA berderet warung-warung berdimensi 1,5 x 1 meter, mereka menjajakan makanan dan minum kepada para pekerja di TPA. Aktivitas pemulung juga tak kalah sibuknya, mereka bekerja tak kenal waktu. Saat armada pengangkut sampah tiba, membawa sisa aktivitas masyarakat di daerah layanan TPA, mereka berlomba-lomba memperebutkan barang-barang yang bagi sebagian orang sudah tidak berarti, tetapi bagi mereka justru memiliki nilai jual tinggi.
Di antara tumpukan sampah yang tingginya setara gedung tersebut itu terdapat kehidupan. Di antara tumpukan sampah ada perekonomian yang bergerak dan orang-orang yang menjalani rutinitas mereka. Bedanya para pekerja di TPA lebih mempertaruhkan keselamatan dibandingkan dengan pekerja yang ada di gedung perkantoran bertingkat.
Dari cerita orang-orang sekitar, sudah beberapa kali terjadi kecelakaan tragis menimpa pemulung. Seorang pemulung yang mencari sampah tiba-tiba tertimpa kloset jongkok rusak yang merenggut nyawanya. Menurut kabar yang beredar, pemulung tersebut berasal dari Jeneponto. Selain itu, ada juga insiden dialami seorang pemulung dari Kabupaten Gowa tertimbun sampah saat beristirahat setelah mencari sampah di tengah teriknya matahari. Ada juga cerita memilukan di mana tangan seorang pemulung terjepit mobil pengangkut sampah akibat rebutan sampah sebelum mobil berhenti sepenuhnya.
Betapapun banyaknya pemulung tidak akan pernah bisa mengatasi tumpukan sampah yang overcapacity. Idealnya pemilahan sampah antara yang masih bernilai dan tidak dilakukan sejak dari sumber. Hal ini juga berperan dalam meminimalisir risiko kecelakaan kerja yang dialami pemulung. Pengelolaan yang baik adalah pengelolaan yang menguntungkan semua pihak, di mana circular economy tetap tercipta tanpa mempertaruhkan keselamatan pihak lain.
Direktur Yayasan Pabbata Ummi (Yaptau), Makmur, lembaga yang concern tentang pengelolaan sampah, menilai ada yang keliru dalam strategi penanganan sampah. Menurutnya persoalan utama pengelolaan sampah di Makassar hanya berorientasi pada proyek, sehingga strategi penanganannya keliru. Koordinasi antara pemerintah dengan pihak swasta yang melakukan pengelolaan sampah berjalan dengan sendiri-sendiri. Belakangan muncul wacana dari pemerintah Sulawesi Selatan untuk membangun TPA Regional Mamminasata, berlokasi di Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa. Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa rencana ini terkendala sejumlah permasalahan.10
Itu bukanlah solusi jika sistem pengelolaan persampahan tidak dilaksanakan berkesinambungan dari upaya pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah.
Mengadakan TPA baru sama saja memindahkan gedung 12 lantai berisi sampah di atas lahan seluas 19,1 hektare ke wilayah baru. Masalah-masalah yang sebelumnya ada di TPA juga ikut bermigrasi ke tempat baru. Dengan kata lain, kerja-kerja semacam ini, tidak lebih dari upaya kerja bakti membangun neraka di tempat hunian lain.
Kita tidak perlu jadi aktivis atau sesuatu yang lebih besar dari itu untuk berkontribusi terhadap persoalan sampah, dengan berpihak pada keberlanjutan lingkungan sudahlah cukup. Segalanya bisa kita mulai dari langkah-langkah kecil, karena langkah kecil jika dilakukan serentak oleh 1.454.960 juta jiwa penduduk Kota Makassar, tentu akan terakumulasi menjadi gerakan-gerakan yang lebih besar.
Konsisten dalam bertindak tentunya sangat sulit, tetapi setidaknya, kita terus berusaha dengan upaya perlawanan kecil di antara gempuran dan iming-iming praktis dari budaya konsumtif yang menggiurkan. Satu hal, kita tidak punya tanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan orang lain bahkan orang terdekat kita, tetapi kesadaran secara pribadi untuk sama-sama belajar tanggung jawab dan mempertimbangkan aktivitas yang menghasilkan produk sampingan (sampah) adalah upaya seumur hidup.
*
Nurul Azmi bergiat di Rumah Saraung. Ia peserta lokakarya Bakkā (Tanahindie - Makassar Biennale) 2024.
Catatan: Tulisan ini juga merupakan hasil proses penelitian awal Nurul Azmi selama lokakarya Bakkā pada Agustus 2024.
[1] Hasbi Zainuddin, https://makassar.terkini.id/sejarah-tpa-antang-dari-panampu-tanjung-bunga-lalu-pindah-ke-tamangapa/, diakses pada 18 Agustus 2024, pukul 19.40 WITA.
[2] Ramadhani, E.D. “Potensi Gas Metana TPA Tamangapa Menggunakan Model Landgem dan IPCC 2006”, Skripsi, (2022), hal 6.
[3] Jarakindonesia, https://www.jarakindonesia.co.id/2024/09/ratusan-ton-sampah-di-tpa-menjadi.html?m=1, diakses tanggal 27 Oktober 2024, pukul 02.00 WITA
[4] Sudarman. “Meminimalkan Daya Dukung Sampah Terhadap Pemanasan Global”, Jurnal Ilmiah Populer dan Teknologi Terapan, Vol 8, No. 1, (2010), hal 53.
[5] Fitrianti, A.F. (2014). “Sistem Pengelolaan Sampah di TPA Tamangapa Antang Makassar”,Skripsi, https://www.scribd.com/doc/221972983/Sistem-Pengelolaan-Sampah-Tpa-Antang.
[6] Waste4Change, https://waste4change.com/blog/bahaya-gas-metana-terhadap-kualitas-udara/, diakses tanggal 18 November 2024, pukul 13.50 WITA.
7 Ikbal, B. “Analisis Dampak Bencana Kebakaran Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa Makassar”, Tesis, (2020), hal 19.
8 Asiri, S., Manaf, M., & Syafri, S. “Pengaruh Keberadaan TPA Antang Terhadap Perubahan Pemanfaatan Ruang di Sekitarnya”, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol. 8, No. 2, (2019), hal 141.
9 Jarakindonesia, https://www.jarakindonesia.co.id/2024/09/ratusan-ton-sampah-di-tpa-menjadi.html?m=1, diakses tanggal 27 Oktober 2024, pukul 02.00 WITA