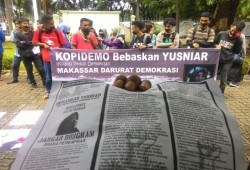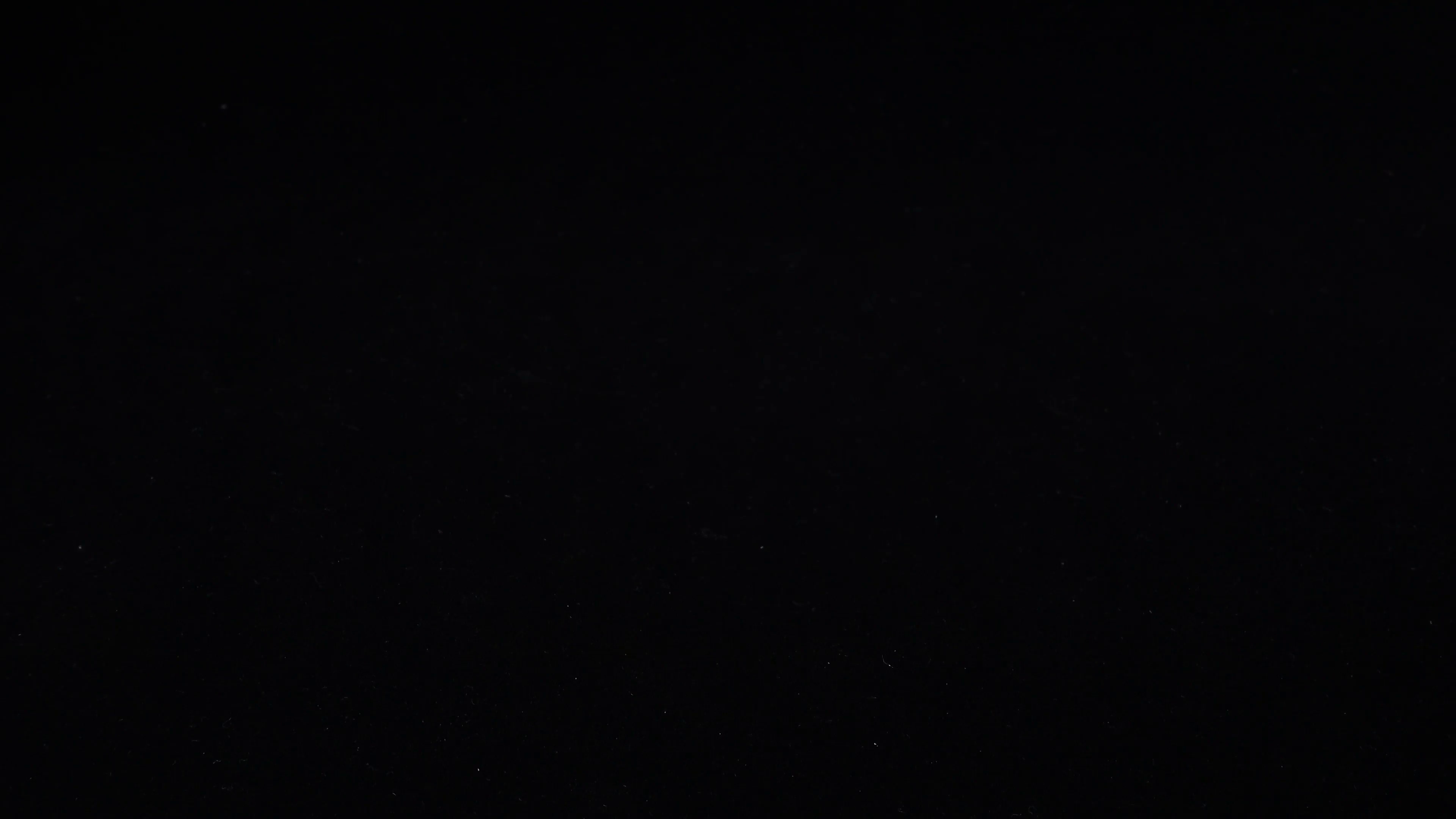Pasar Butung pada Suatu Ahad Tahun 2010
Aku membuka lagi sebuah peta Makassar ukuran A nol dan menghamparkan di lantai, seperti membentangkan selembar tikar yang tergulung. Di sisi kanan atas peta itu tertera angka 1955. Artinya peta ini sudah berusia 55 tahun. Aku menghitung satu per satu pasar di Makassar pada tahun itu. Yang ada: Pasar Butung, Pasar Tjidu, Pasar Kalimbu, Pasar Baru, dan Pasar Lette.
Aku berusaha mencari nama Pasar Terong, pasar lokal terbesar di Makassar. Tapi yang kutemukan hanya pasar pelelangan ikan di Gusung dan di Kampung Baru. Ah, aku hanya berandai-andai. Pasar Terong belum ada saat itu bukan? Terong baru dikenal pada tahun 1970.
Suatu hari aku mendengar kisah dari Haji Tula, seorang pedagang tua. Ia mulai berdagang di Pasar Kalimbu tahun 1958. Ia berdagang buah saat itu dan hingga kini masih berdagang buah di Pasar Terong. Tapi sekarang ini lebih banyak istirahat. Ia sudah berpinak dan bercucu. Dua orang anaknya merupakan punggawa buah-buahan asal Takalar.
Menurutnya, cikal bakal berdirinya pasar Terong dimulai dari keramaian orang berjualan di Jalan Bayam hingga ke Jalan Bawakaraeng. Belakangan luasan pasar bertambah seiring pertumbuhan kota dan pertambahan penduduk. Sekitar tahun 1965 terjadi kebakaran sejumlah rumah penduduk. Beberapa tahun kemudian, di bekas lokasi kebakaran itu Walikota Daeng Patompo mendirikan bangunan pasar inpres yang kemudian dinamai Pasar Terong.
Tampaknya, meningkatnya urbanisasi pada rentang dekade 60-an ini disebabkan oleh berkecamuknya desa-desa dataran tinggi di Sulawesi Selatan. Pasukan Qahhar Mudzakkar sejak menolak kebijakan militer pusat memekikkan pemberontakan. Desa-desa berkecamuk begitu Militer Jawa datang bermaksud menumpas pemberontakan Qahhar. Para penduduk desa meninggalkan kampung dan masuk kota. Salah satu pilihan yang memungkinkan saat itu adalah hijrah ke Makassar.
(Jika saat itu saya sudah remaja, tentu saya akan memilih berada di pegunungan itu dan berdiri di belakang Qahhar ketimbang di kota ini. Saya percaya bahwa ia memiliki semangat pemberontakan untuk memperbaiki keadaan. Sayangnya Qahhar gagal dan mati tertembak di Sungai Lasolo. Aku tinggal membaca atau mendengar kisah-kisahnya dari belasan orang tua yang pernah kutemui di Desa Tassese di Gowa, Kompang di Sinjai, Barae di Soppeng, Latimojong, dan Palopo di Luwu atau Oloholoho di Kolaka.)
Aku menggulung peta. Hari ini aku bersama teman-teman akan tur ke sejumlah pasar lokal di Makassar. Beberapa waktu lalu aku melihat sebuah foto saat Pasar Butung baru saja rampung dibangun Pemerintah Kolonial Belanda. Bangunannya berupa lods sederhana dan tertata apik. Tidak detail memang. Tapi, setidaknya, bisa dibayangkan pasar ini pasti ramai setiap harinya. Pada tahun itu, pusat kota tepat di kawasan ini, yang terletak tak jauh dari Fort Rotterdam sebagai wilayah kelas satu orang-orang Belanda.
Sebuah dokumen yang pernah kubaca di Badan Arsip Daerah menyebutkan, di tahun yang sama, 1 September 1917 tepatnya, sebuah peraturan tentang pasar dikeluarkan untuk menjamin tertatanya pasar ini dengan baik. Surat edaran itu bernomor 15. Pengesah surat itu adalah W. Fryling. Pokok pengaturannya yaitu pendayagunaan lingkungan pasar dengan model penarikan retribusi.
Retribusi dalam surat itu ditulis dengan bahasa lokal ‘sussung pasara’ dengan pengawasan yang ketat dan penggunaan yang maksimal untuk berbagai kepentingan tata kelola pasar lokal. Aku pikir, betapa pemerintah kolonial saat itu benar-benar menata pasar. Retribusi ditarik benar-benar untuk kepentingan tata kelola pasar.
Tapi kini, pengelolaan pasar sepertinya lebih sebagai upaya elit mengontrol pendapatan harian dari pedagang melalui sussung pasara’ untuk kepentingan kelompok tertentu ketimbang untuk menata pasar. Buktinya, sulit sekali saat ini menemukan satu dari 57 pasar (besar dan kecil) di Makassar yang terkelola apik, selain Pasar Bacan di permukiman Tionghoa. Di sana hanya sebaris jalan diduduki seratusan pedagang sejak subuh hingga pukul 10 pagi. Lepas itu, mereka akan berbenah dan tepat pukul 12 siang jalan itu bersih kembali dan kendaraan pun bisa lalu-lalang.
Kami tiba di Pasar Butung tepat pukul 08.00. Sebagian kawan yang turut tur sudah di sana. Pasar ini usianya mendekati 100 tahun. Bentuknya tak serupa foto itu lagi. Sudah sekian kali terjadi perubahan bentuk bangunan. Kini ia juga bukan lagi pasar basah yang menjual sayur mayur, ikan segar, dan segala kebutuhan pangan warga kota. Bangunannya kini serupa department store berlantai lima.
Pasar Butung terletak di Kampung Butung, di antara pertemuan Jalan Tentara Pelajar dan Jalan Nusantara, ujung utara Jalan Sulawesi (dulu bernama Tempel Straat dan Paseer Straat), Jalan Kalimantan, dan Jalan Butung. Jika sembilan puluhan tahun lalu bangunan di sekitarnya adalah perpaduan bangunan khas Eropa dan Tionghoa, kini didominasi oleh bangunan rumah toko bertingkat dua, tiga dan empat yang semua jendelanya dilindungi tralis besi yang sangat rapat. Tralis besi itu menunjukkan sisa traumatik dua kali peristiwa ‘pengganyangan’ Tionghoa yang pernah terjadi di Makassar: Peristiwa ‘Toko La’ tahun 1978 dan ‘pembunuhan anak seorang dosen IAIN Sultan Alauddin’ 1997’.
Menurut salah seorang informan yang kami temui, pasar ini dulunya bukan pusat grosir. Ia selayak pasar ‘tradisional’ lainnya. Dari dua gapura yang ada, menunjukkan bahwa pasar ini pernah mengalami revitalisasi, yakni tahun 1999 dan 2002. Belum ada keterangan rinci lanjutan bagaimana proses perubahan pasar sejak awal hingga kini.
Kami mengelilingi pasar dan mengamati bangunan sekitar. Beberapa bangunan tua masih berdiri. Tapi satu di antaranya baru saja dirubuhkan. Bangunan itu di Jalan Sulawesi, tepat di sisi kiri lorong menuju Kampung Butung, tempat Masjid Mubarak berada. Bangunan itu sudah terhimpit dua ruko berlantai empat. Ada sepuluhan bangunan tua yang tersisa. Hanya beberapa yang tampaknya masih baik, seperti bangunan yang kini menjadi toko/bengkel Matahari Motor dan Mandiri Motor. Itupun bila tampak depan bukan lagi berwujud jendela-jendela besar, melainkan sekadar papan reklame yang menutupi sepertiga bangunan rumah.
Di pengkolan jalan raya ini, tampak ‘wajah’ bangunan kedai kopi yang peraciknya beretnis Tionghoa. Makassar tempo doeloe memang terkenal dengan para peracik kopi etnis Tionghoanya. Bahkan, sebuah foto yang menunjukkan bahwa pernah ada perkumpulan para peracik kopi ini. Sayangnya, karena masih terlalu pagi, kedai ini belum terbuka.
Akhirnya kami putuskan masuk ke dalam Pasar Butung. Tak berapa lama, sudah terdengar bunyi puluhan genset. Sambil menduga-duga kami terus melangkah. Menaiki anak tangga selatan ini, kami melihat gerai BNI (Bank Negara Indonesia) sedang menata berbagai keperluan pemasaran. Demikian pula banyak pedagang lalu lalang dan banyak di antaranya sedang menggantung pakaian jualan. Di lantai dasar, kami menuruni anak tangga kanan. Di bagian ini kios lebih padat dan hampir seluruhnya terbuka dan ramai dengan kegiatan menata pakaian jualan. Pasar ini memang sudah dikenal sebagai pusat grosir pakaian.
Kios-kios di lantai memiliki nama. Beberapa di antaranya adalah ‘Stand Firman’, ‘Stand Hairul Akbar’, ‘Stand Suka Maju’, ‘Stand An Nur’, ‘Stand Hj Anti’, ‘Stand Hermawan’, ‘Stand H.A. Kadir’, ‘Ading Collection’, dan seterusnya. Beberapa papan penunjuk juga menjelaskan jenis jualan seperti ‘aneka sarung’, ‘moslem style’, ‘baju sekolah’, ‘baju anak-anak’, dan sebagainya.
Ada dua buah elevator menuju lantai dua. Namun keduanya sudah berkarat dan tidak berfungsi. Dibandingkan dengan yang ada Pasar Terong, elevator di Pasar Butung masih lebih baik. Di Pasar Terong, bukan hanya tangga penuh tanah dan karat, mesinnya pun hilang dicuri orang!
Menurut laki-laki yang sedang menata ‘stand H.A. Kadir’, genset mulai digunakan sejak pasar ini tak sanggup lagi memenuhi daya listrik bagi seluruh pedagang. Kini dibatasi hanya boleh maksimal 80 watt. Bila ada yang memakai lebih, seluruh listrik Pasar Butung akan padam.
Dampak kebijakan pengelola pasar ini terasa bagi pedagang lantai dasar dan satu. Di lantai dasar yang tak berventilasi, ramai pengunjung akan membuat panas ruangan itu bila tidak disediakan kipas angin. Di sinilah fungsi genset sebagai tenaga tambahan agar pelanggan merasa nyaman saat berbelanja.
Di lantai dua, hanya beberapa pekerja membereskan baju-baju dan pernik pakaian lainnya. Mereka buruh, bukan pemilik kios. Sang pemilik akan datang beberapa jam lagi setelah semuanya beres. Sebagian saja kios yang buka. Mengapa di hari Minggu ini pedagang terlambat buka kios mereka? Rupanya memang ada hanya sedikit pedagang berdagang di lantai dua. Banyak kios tersedia, namun pembeli sudah demikian sepi. Mereka hanya datang pada hari menjelang Lebaran dan Natal. Selebihnya mereka membiarkan saja kios ini tertutup.
Di lantai dua ini ada juga elevator menuju lantai tiga (dan demikian terlihat dari bawah elevator menuju lantai empat). Sayangnya, kami tidak bisa naik karena pintu kaca di atas sana tertutup.
“Penjual apa saja di atas?” tanya aku pada seorang perempuan yang bersibuk di kiosnya.
“Di atas cuma ada sundel bolong,” seloroh perempuan itu.
Kami terpingkal-pingkal.
Menurut Enal, rekan yang turut dalam tur ini, saudagar Wajo adalah ‘penguasa’ di area ini. Mereka mendominasi usaha di sini dengan cara saling menjaga bisnis sesama etnis.
Karena tak bisa lagi melanjutkan ke lantai berikutnya, kami pun memilih keluar gedung ini. Panas dan pengap membuat kami yang tak terbiasa kepayahan dan membutuhkan udara segar. Saat berjalan aku membayangkan lagi betapa perencana bangunan pasar masa lalu, katakanlah masa awal abad dua puluh ini, jauh lebih manusiawi dengan mendesain bangunan yang nyaman, baik penjual maupun pembeli.
Seorang perencana kota kolonial Thomas Karsten, juga dikenal sebagai arsitektur pasar klasik, banyak menjelaskan bagaimana sebuah kota ditata dari ketidakteraturannya (unruly), termasuk para pedagang yang mengisi badan-badan jalan (street vendors). Dalam ‘Explanatory Memorandum in Wertheim 1958’, ia menceritakan alasan-alasan maraknya pembangunan pasar kota pada tahun-tahun yang dikenal sebagai ‘zaman normal’, yakni dekade 1920-1930. Tujuannya adalah mengendalikan ketidakteraturan pedagang jalanan (street vendors) atau kini lazim disebut pedagang kaki lima.
Dias Pradadimara, dalam 2 artikel tentang sejarah Kota Makassar menjelaskan tahun-tahun ‘keemasan’ kota ini. Berbagai fasilitas yang memanjakan penduduk khususnya para pendatang yang berkunjung atau menetap untuk keperluan bisnis ataupun berlibur tersedia. Dengan merujuk pada sebuah buku petunjuk turis masa itu, Pradadimara memaparkan bahwa sudah terdapat beberapa perusahaan dan konsulat asing yang bekerja di kota Makassar karena lengkapnya fasilitas di kota ini. Bahkan, dari aspek penerangan pun, kota ini disinyalir sebagai kota yang paling diterangi di Hindia Belanda dengan persediaan tenaga listrik yang disuplai dari Makassar dan Sungguminsa (Dias Pradadimara, 2007).
Aku menarik nafas panjang begitu keluar dari gedung ini. Sayang, suara genset yang menderu mengharuskan kami memilih bersantai jauh dari puluhan genset di dalam pasar.
Tak sampai setahun sejak kunjungan kami di Pasar Butung, seorang kawan mengirim pesan singkat ke telepon selulerku: Pasar Butung terbakar! Saat itu menjelang Natal 2010 dan tak sedikit pedagang sudah mempersiapkan barang guna memenuhi kebutuhan sandang para pembeli. Aku bergumam, satu lagi pasar lokal terbakar.[]